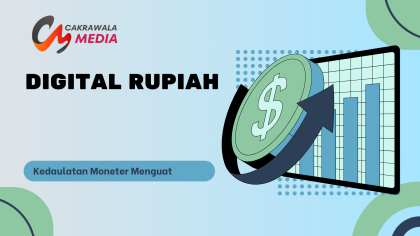Di Jawa Tengah, senja pada bulan Ramadan bukan sekadar penanda waktu untuk membatalkan lapar. Ketika dentum bedug bertalu dan suara azan Magrib bersahutan dari corong-corong masjid yang berdekatan, sebuah transformasi sosial yang unik dimulai. Jika di kota-kota megapolitan berbuka puasa sering kali terjebak dalam hiruk-pikuk komersialisme mal, di tanah Jawa—mulai dari pesisir utara hingga ke pedalaman Vorstenlanden—Ramadan justru menghidupkan kembali sel-sel komunalitas yang mungkin sempat layu oleh rutinitas modern.
Budaya pasca-buka puasa di Jawa Tengah adalah sebuah dialektika yang cantik antara ketaatan religius dan warisan agraris-komunal. Di sini, religiositas tidak tampil dalam wajah yang kaku, melainkan cair dalam cangkir-cangkir teh panas dan bincang-bincang di selasar mushala.
Tradisi Jaburan: Diplomasi Kudapan di Selasar Mushala
Secara historis, Islam masuk ke Nusantara, khususnya Jawa, melalui pendekatan kebudayaan yang dilakukan oleh Wali Songo. Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, misalnya, memahami bahwa perut adalah pintu masuk yang efektif menuju hati. Warisan ini mengkristal dalam tradisi Jaburan.
Jaburan—berasal dari istilah lokal untuk kudapan atau penganan ringan—adalah fenomena pasca-Salat Tarawih yang masih lestari di kantong-kantong pedesaan dan kampung kota. Berbeda dengan takjil yang dimakan saat berbuka, Jaburan disajikan sebagai bentuk apresiasi bagi jamaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah malam. Secara sosiologis, Jaburan adalah manifestasi nyata dari konsep sedekah jariyah. Warga secara sukarela, bergiliran sesuai jadwal, membawa nagasari, mendoan, atau jadah ke masjid.
Di sini, data lapangan menunjukkan sebuah pola redistribusi pangan yang unik. Jaburan menghapus batas antara si kaya dan si miskin. Di atas lantai ubin masjid yang dingin, semua orang duduk melingkar (lesehan) menikmati hidangan yang sama. Tidak ada hierarki sosial dalam piring plastik berisi gorengan. Inilah forum paling jujur di mana masalah-masalah kampung didiskusikan secara informal sembari menunggu waktu tadarus dimulai.
Angkringan dan Etos “Nasgithel”
Setelah urusan spiritual di masjid usai, denyut kehidupan Jawa Tengah berpindah ke pinggir jalan. Di Solo, Klaten, hingga Yogyakarta, fenomena Angkringan atau HIK (Hidangan Istimewa Kampung) menjadi pusat gravitasi sosial pasca-buka.
Angkringan adalah ruang publik paling egaliter yang pernah diciptakan dalam sejarah sosial Jawa. Di bawah naungan tenda terpal dan cahaya lampu minyak (atau bohlam redup), seorang buruh pabrik bisa duduk berdampingan dengan pejabat daerah atau akademisi. Mereka dipersatukan oleh satu elemen penting: Teh Nasgithel (Panas, Legi, Kenthel).
Bagi masyarakat Jawa Tengah, teh bukan sekadar minuman; ia adalah simbol kehidupan. Rasa pahit yang kental beradu dengan manisnya gula batu mencerminkan filosofi hidup yang penuh cobaan namun tetap harus dirasakan manisnya. Di angkringan pasca-buka, “diplomasi meja kayu” terjadi. Segala isu, mulai dari harga pupuk, gosip politik nasional, hingga skor pertandingan sepak bola, dibahas dengan nada bicara yang rendah namun mendalam. Angkringan berfungsi sebagai katup pengaman sosial (social safety valve) yang meredam ketegangan hidup melalui obrolan yang santai namun bermakna.
Lanskap Suara dan Penjagaan Malam
Malam Ramadan di Jawa Tengah juga memiliki identitas auditif yang khas. Setelah pukul sembilan malam, suara Tadarus Al-Qur’an mulai mengalun. Bagi orang luar, ini mungkin sekadar suara lewat pengeras suara, namun bagi masyarakat lokal, ini adalah “napas” malam.
Secara teknis, tadarus adalah ibadah personal, namun di Jawa, ia bermutasi menjadi kegiatan kolektif-edukatif. Para remaja masjid belajar mengaji, sementara yang lebih tua menyimak. Di sudut lain, para pemuda mulai menyiapkan alat musik bambu atau perkusi sederhana untuk tradisi Kotekan atau Kolo-kolo.
Secara faktual, aktivitas ini memiliki fungsi ganda: spiritual dan keamanan. Dengan adanya kelompok-kelompok yang terjaga hingga larut malam di berbagai titik, tingkat kriminalitas di pemukiman warga secara statistik menurun selama bulan Ramadan. Gotong royong untuk “menjaga malam” demi memastikan tetangga tidak kesiangan saat sahur adalah bentuk solidaritas organik yang jarang ditemukan di masyarakat individualis.
Merawat Akar di Tengah Perubahan
Budaya pasca-buka puasa di Jawa Tengah adalah bukti bahwa modernitas tidak harus menghancurkan tradisi. Meskipun gawai dan internet telah masuk ke pelosok desa, keinginan masyarakat untuk berkumpul secara fisik (guyub) tetap tak tergantikan.
Esensi dari seluruh ritual malam ini adalah koneksi. Ramadan menjadi katalisator yang menarik orang keluar dari rumah-rumah mereka yang tertutup, mengajak mereka duduk bersama di emperan toko atau serambi masjid. Pada akhirnya, tradisi di Jawa Tengah ini mengajarkan kita sebuah kebenaran sederhana: bahwa keberagamaan yang paling indah adalah keberagamaan yang mampu mempererat tali persaudaraan manusia, lewat doa-doa yang dilangitkan dan lewat teh hangat yang disesap bersama di bumi.