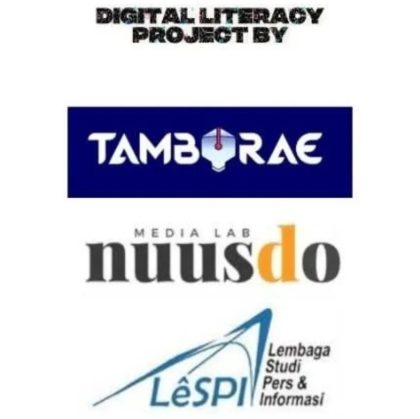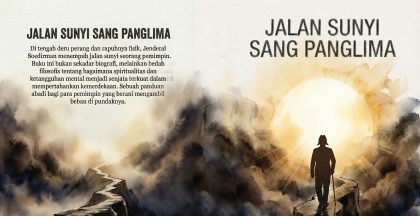Oleh: Bastomi
Partai politik, sebagai pilar fundamental demokrasi, mengemban amanah krusial: mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem politik dan melahirkan pemimpin bangsa yang kompeten. Namun, di Indonesia, dua isu mendalam terus membayangi peran vital ini: fenomena partai yang mengusung calon pemimpin dari luar kader internal, serta tuntutan berkelanjutan untuk menaikkan bantuan keuangan negara bagi partai politik. Kedua isu ini, yang tampak terpisah, sejatinya saling terkait dalam jaring kompleks yang memengaruhi kesehatan demokrasi dan integritas tata kelola pemerintahan.
Ketika Kaderisasi Gagal: Fenomena “Calon Instan” dan Oligarki Partai
Pertanyaan mendasar muncul: benarkah partai yang mengusung calon ketua umum atau pemimpin dari luar kader berarti kegagalan sistem pengkaderan partai tersebut? Analisis mendalam menunjukkan bahwa praktik ini adalah gejala nyata dari kerapuhan institusional. Kaderisasi, yang secara fundamental berarti proses strategis mempersiapkan “embrio” calon pemimpin yang siap melanjutkan misi organisasi, seringkali tidak berjalan optimal. Kader idealnya adalah pendukung yang memahami ideologi partai, siap berjuang meraih kekuasaan, dan menjadi penghubung esensial antara partai dan konstituen.
Namun, realitas politik Indonesia diwarnai oleh sejumlah tantangan yang menghambat kaderisasi efektif:
Rekrutmen yang Lemah dan Tertutup: Banyak partai belum memiliki kerangka kaderisasi yang jelas, cenderung tertutup, elitis, dan non-meritokratis. Seleksi calon seringkali diumumkan mendadak, tanpa prosedur internal yang kuat atau evaluasi publik. Ini menciptakan lingkungan di mana talenta internal tidak terpelihara, memaksa partai mencari kepemimpinan dari luar.
Prevalensi “Kader Instan” dan “Politik Kekerabatan”: Kelemahan kaderisasi berkontribusi pada munculnya “kader instan”—figur populer yang dicalonkan berdasarkan ketenaran daripada proses kaderisasi yang semestinya.
Praktik ini menimbulkan ketidakadilan bagi kader berdedikasi yang telah meniti karir dari bawah. Bersamaan dengan itu, “politik kekerabatan” membatasi akses kader non-keluarga ke posisi strategis, mengonsentrasikan kekuasaan pada kelompok elit yang seringkali mengutamakan kepentingan pribadi.
Dominasi Ketua Umum dan Struktur Oligarkis: Pengaruh luar biasa ketua umum partai seringkali menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan, memusatkan kekuasaan pada segelintir elit atau satu figur sentral. Banyak partai yang terbentuk dari atas ke bawah, menumbuhkan ketergantungan pada figur karismatik (misalnya, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri). Dominasi personalistik ini menghambat institusionalisasi partai dan sirkulasi kepemimpinan yang sehat.
Pragmatisme di Atas Kualitas: Partai seringkali memprioritaskan kemenangan elektoral, memilih figur populer dengan kapasitas finansial substansial, seringkali mengorbankan kualitas dan kapabilitas calon. Pragmatisme ini menyebabkan penurunan komitmen ideologis partai.
Implikasi dari nominasi non-kader ini sangat serius. Ini memperkuat dominasi oligarki, menekan demokrasi internal, dan menghasilkan lanskap politik yang kurang kompetitif, seperti munculnya calon tunggal atau “koalisi gemuk”. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan penurunan keterlibatan publik dan apatisme terhadap partai politik, merusak esensi demokrasi itu sendiri.
Dilema “Harga Suara”: Antara Kebutuhan dan Akuntabilitas
Di sisi lain, tuntutan untuk menaikkan “harga suara” sebagai instrumen dana bantuan negara bagi partai politik juga menjadi sorotan. Bantuan keuangan negara diatur oleh kerangka hukum yang komprehensif, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2011 dan berbagai Peraturan Pemerintah serta Permendagri. Dana ini dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh partai dalam pemilu, dan dicairkan setiap tahun dari APBN atau APBD.
Sejak 2005, besaran bantuan per suara sah telah beberapa kali disesuaikan. Dari Rp 108 per suara, naik signifikan menjadi Rp 1.000 per suara pada 2018. Namun, beberapa pihak, seperti PKS, mengusulkan kenaikan lebih lanjut hingga Rp 10.000 per suara. Bahkan di tingkat daerah, ada yang sudah menetapkan Rp 10.000 per suara, seperti Kota Pasuruan.
Alasan di balik tuntutan kenaikan ini beragam:
Kebutuhan Operasional yang Besar: Partai membutuhkan dana besar untuk menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk kegiatan kesekretariatan dan pendidikan politik.
Macetnya Iuran Anggota dan Donasi Publik: Sumber utama masalah keuangan partai adalah macetnya iuran anggota dan donasi publik, sebagian karena peran partai yang belum optimal dan citra yang buruk di mata masyarakat.
Mengurangi Ketergantungan pada Dana Ilegal: Kenaikan dana diharapkan dapat mengurangi ketergantungan partai pada sumber pendanaan tidak jelas atau korup, yang sering memicu korupsi politik.
Dana bantuan ini diprioritaskan untuk pendidikan politik (minimal 60%) dan operasional kesekretariatan. Mekanisme pertanggungjawaban pun ketat, dengan laporan yang harus disampaikan kepada BPK setiap tahun.
Namun, kenaikan bantuan ini juga memiliki potensi dampak negatif. Tanpa pembenahan mendasar dalam tata kelola partai, dana yang lebih besar hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara. Survei menunjukkan bahwa peningkatan dana belum tentu mencegah korupsi. Bahkan, dapat memperkuat ketergantungan partai pada negara, menggeser fokus dari melayani konstituen menjadi mendekati pemerintah.
Lingkaran Setan: Kaderisasi, Dana, dan Korupsi Politik
Hubungan antara lemahnya kaderisasi, sistem bantuan keuangan, dan korupsi politik adalah sebuah lingkaran setan. Mahalnya biaya politik, terutama “mahar politik” (pembelian nominasi) dan “jual beli suara,” berakar pada masalah rekrutmen internal partai. Modal awal yang besar ini mendorong calon untuk memenangkan pemilu demi mengembalikan modal, seringkali melalui praktik korupsi setelah menjabat.
Data KPK menunjukkan bahwa 32% atau 179 tersangka korupsi adalah aktor politik. Korupsi politik, yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dapat terjadi sebelum, selama, dan setelah menjabat.
Kasus-kasus korupsi yang melibatkan ketua umum partai, seperti Lutfi Hasan Ishaaq (PKS), Anas Urbaningrum (Demokrat), Setya Novanto, dan Romahurmuzy (PPP), menjadi bukti nyata masalah ini.
KPK menekankan bahwa politik uang dapat menjadi prekursor korupsi, karena kebutuhan untuk mengembalikan biaya pemilu yang tinggi mendorong aktor politik terlibat dalam praktik korupsi. Manajemen pemerintahan yang korup adalah salah satu hasil langsung dari politik uang. Ini merusak paradigma bangsa, mengikis nilai-nilai fundamental, dan menyebabkan pandangan sinis terhadap politik.
Akar penyebab dari semua ini adalah fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai yang belum selaras dengan sistem berbasis meritokrasi. Tanpa meritokrasi, pejabat partai rentan terjebak dalam strategi jangka pendek untuk akuisisi sumber daya, yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Menuju Demokrasi yang Lebih Sehat
Fenomena nominasi non-kader dan tuntutan kenaikan dana partai adalah cerminan dari tantangan struktural yang dihadapi demokrasi Indonesia. Kegagalan kaderisasi internal menciptakan kekosongan kepemimpinan yang sering diisi oleh figur eksternal, sementara kebutuhan finansial partai yang besar membuka celah bagi praktik korupsi.
Untuk mengatasi ini, reformasi menyeluruh sangat dibutuhkan. Partai politik harus didorong untuk menerapkan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih transparan, meritokratis, dan demokratis. Pendidikan politik internal harus diperkuat, dan dominasi oligarki dibatasi.
Sementara itu, peningkatan bantuan keuangan negara harus disertai dengan pengawasan ketat, reformasi tata kelola, dan diversifikasi sumber pendanaan legal. Tanpa pembenahan fundamental ini, kenaikan dana semata hanya akan menjadi pemborosan dan tidak efektif dalam mencegah korupsi atau meningkatkan kualitas kaderisasi.
Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan partai politik untuk bertransformasi menjadi institusi yang akuntabel, transparan, dan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas dari dalam jajarannya sendiri, bukan sekadar kendaraan untuk meraih kekuasaan.