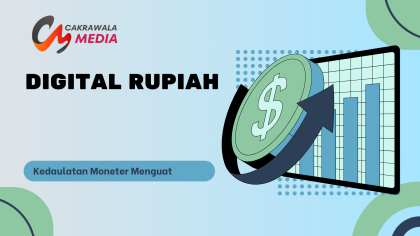Jumat, 30 Januari 2026, akan dicatat sebagai hari paling kelam sekaligus paling “ganjil” dalam sejarah pasar modal Indonesia. Bukan hanya karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkapar dihajar rebalancing MSCI, tetapi karena apa yang terjadi di Gedung Sumitro Djojohadikusumo beberapa jam setelah pasar tutup.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, mengundurkan diri secara serentak. Alasan resminya: “tanggung jawab moral” atas guncangan pasar.
Namun, bagi siapa saja yang memahami anatomi kekuasaan di republik ini, narasi “tanggung jawab moral” itu terdengar sumbang. Di negara di mana pejabat korup pun enggan mundur, sulit mempercayai bahwa sekumpulan teknokrat prudent mundur massal hanya karena fluktuasi indeks.
Investigasi digital mendalam menunjukkan bahwa jatuhnya IHSG hanyalah pintu masuk—sebuah pretext—untuk sebuah operasi yang jauh lebih besar: Penyingkiran hambatan regulasi demi memuluskan jalan “Super-Holding” negara menguasai infrastruktur pasar modal secara mutlak.
Kambing Hitam Bernama MSCI
Narasi publik diarahkan untuk percaya bahwa OJK gagal mengantisipasi dampak rebalancing indeks MSCI yang memicu capital outflow gila-gilaan. Benar, pasar crash. Namun, menghukum regulator atas keputusan alokasi aset global adalah hal yang absurd.
Kebenaran yang lebih pahit tersaji di balik layar. Para komisioner ini kemungkinan besar tidak “mengundurkan diri”, melainkan “diminta mundur” karena menolak—atau setidaknya menghambat—agenda agresif Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dan raksasa baru bernama BPI Danantara.
Inarno Djajadi dan Mahendra Siregar dikenal sebagai figur yang konservatif. Mereka adalah penjaga gawang tua yang memegang prinsip prudential banking dan independensi pasar. Di mata rezim pertumbuhan agresif saat ini, kehati-hatian mereka adalah “rem tangan” yang harus dilepas.
Sang Monster Baru “Danantara”
Pemicu utama konflik ini mengerucut pada satu entitas: Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara).
Lembaga ini didesain sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) super-body. Ambisinya tidak main-main: mengelola aset BUMN dan melipatgandakan valuasinya. Namun, Danantara butuh panggung. Kepala Danantara, Rosan Roeslani, secara terbuka telah menyatakan minatnya agar Danantara menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI).
Di sinilah letak “dosa” Inarno Djajadi. Di bawah aturan lama (POJK No. 3/2021), pemilik saham BEI wajiblah Anggota Bursa (Perusahaan Sekuritas). Aturan ini adalah benteng independensi agar bursa tidak dikuasai oleh pihak eksternal. Inarno dan tim OJK lama bertahan pada prinsip ini.
Namun, UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) telah membuka kotak pandora bernama Demutualisasi. Bursa akan diubah dari badan nirlaba menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang mengejar untung.
Dengan mundurnya Inarno, jalan bagi Danantara kini terbuka lebar. Plt. Ketua OJK dan jajaran barunya nanti memiliki tugas mendesak: segera merampungkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang membolehkan “Lembaga Pemerintah” (baca: Danantara) memiliki saham bursa.
Kematian “Check and Balance”
Mengapa kita harus cemas jika Danantara memiliki BEI?
Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola. Danantara adalah pemilik klub (mengelola BUMN seperti Telkom, BRI, Mandiri). BEI adalah penyedia stadion dan wasitnya. Jika Danantara juga membeli BEI, maka Pemilik Klub resmi menjadi Pemilik Stadion dan Bos Wasit.
Ini adalah definisi klasik dari State Capitalism tanpa firewall.
Jika skenario ini terjadi:
Siapa yang akan menghukum BUMN nakal? Jika emiten BUMN memanipulasi laporan keuangan, apakah BEI (milik Danantara) berani menindak “saudara kandungnya” sendiri?
Listing Paksa: Ada indikasi kuat bahwa eksekutif menekan OJK untuk mempermudah IPO anak-usaha BUMN yang fundamentalnya “merah” (tidak layak) demi mengejar target valuasi aset Danantara. Tanpa Inarno sebagai penyaring, sampah pun bisa dijual mahal di bursa.
Dana Pensiun Sebagai Bahan Bakar
Aspek paling mengerikan dari manuver ini adalah sumber dananya. Di tengah kepanikan pasar akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi mengejutkan: menaikkan batas investasi Dana Pensiun dan Asuransi di saham hingga 20%, khususnya di LQ45.
Instruksi ini keluar “seminggu jadi”, memunggungi prinsip manajemen risiko (Stress Test) yang selama ini dijaga OJK.
Polanya terbaca jelas:
- Asing kabur (jual saham).
- IHSG jatuh.
- Pemerintah butuh pembeli siaga.
Dana Pensiun (Taspen, BPJS, Asabri) “dipaksa” masuk menampung barang jualan asing tersebut atas nama “patriotisme ekonomi”.
Ini adalah skema transfer risiko dari investor asing ke uang pensiun rakyat Indonesia. Jika pasar tidak bangkit, atau jika BUMN yang dibeli sahamnya ternyata keropos, maka yang akan hangus adalah uang jaminan hari tua jutaan pekerja.
Kesimpulan: Kudeta Regulasi
Apa yang kita saksikan di akhir Januari 2026 ini bukanlah sekadar pergantian pejabat. Ini adalah sebuah Kudeta Regulasi.
Pemerintah, melalui Danantara dan Kementerian Keuangan, sedang membangun ekosistem tertutup:
- Negara yang memiliki emiten (BUMN).
- Negara yang memiliki bursa (BEI via Danantara).
- Negara yang mengatur pengawasan (OJK Baru).
- Negara yang menyediakan likuiditas (Dana Pensiun).
Dalam ekosistem ini, transparansi adalah musuh, dan check and balance adalah hambatan. Pimpinan OJK yang lama mungkin bukan malaikat, tapi mereka adalah rem terakhir yang mencegah pasar modal kita menjadi kasino milik negara.
Sekarang rem itu telah dicopot. Mesin ekonomi digeber kencang di jalanan menurun. Kita, rakyat biasa, hanya bisa berharap tidak ada tikungan tajam di depan.